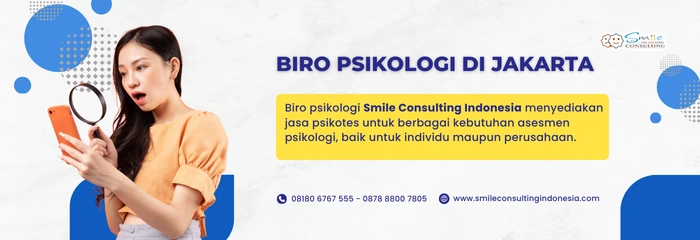Di tengah derasnya arus informasi yang mengalir tanpa henti setiap hari, manusia semakin dihadapkan pada tantangan untuk menyaring, memahami, dan memproses informasi secara objektif. Namun, di balik semua itu, ada satu hambatan psikologis yang seringkali bekerja diam-diam namun sangat kuat yaitu bias konfirmasi (confirmation bias). Fenomena ini bukan hanya memperkuat keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi bahan bakar utama penyebaran disinformasi dan hoaks, bahkan di kalangan orang yang cerdas sekalipun.
Bias konfirmasi adalah kecenderungan seseorang untuk lebih memperhatikan, mencari, dan mengingat informasi yang sejalan dengan keyakinan atau opini yang telah dimiliki sebelumnya, sambil mengabaikan atau menolak informasi yang bertentangan. Fenomena ini pertama kali dikemukakan oleh psikolog kognitif Peter Wason pada tahun 1960-an melalui eksperimennya yang menunjukkan bahwa individu lebih cenderung mencari bukti yang menguatkan hipotesis awal mereka ketimbang membuktikan bahwa hipotesis itu mungkin salah (Wason, 1960).
Dalam konteks digital saat ini, bias konfirmasi menjadi semakin berbahaya. Media sosial yang bersifat algoritmik cenderung menyuguhkan konten yang sesuai dengan perilaku klik dan pencarian sebelumnya. Hal ini menciptakan semacam “gelembung informasi” atau echo chamber, di mana seseorang terus-menerus terpapar oleh informasi yang memperkuat pandangannya sendiri. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis menurun karena dunia yang dilihat menjadi sempit dan homogen.
Misalnya, seseorang yang sudah percaya bahwa vaksin itu berbahaya akan lebih mudah percaya pada artikel atau video YouTube yang menyatakan efek negatif vaksin, meskipun bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Bahkan ketika orang tersebut berhadapan langsung dengan data dari sumber kredibel seperti WHO atau jurnal medis, mereka bisa saja menolaknya dengan alasan bahwa informasi tersebut berasal dari institusi yang dianggap “tidak netral” atau memiliki agenda tersembunyi. Fenomena ini juga diperkuat oleh riset dari Nickerson (1998) yang menyatakan bahwa bias konfirmasi dapat membuat seseorang menolak fakta dengan sengaja jika fakta tersebut mengancam identitas atau keyakinan dasarnya.
Dalam dunia politik, bias konfirmasi memainkan peran besar dalam polarisasi masyarakat. Orang-orang cenderung mengikuti narasi media yang sesuai dengan preferensi politik mereka. Ketika berita palsu atau hoaks disebarkan, tidak semua pembaca akan bersikap skeptis. Justru, berita yang mengandung muatan ideologis yang cocok dengan mereka akan disebarkan lebih luas, tanpa verifikasi. Hal ini dibuktikan oleh Pennycook dan Rand (2018) dalam studinya yang menemukan bahwa pengguna media sosial lebih mungkin membagikan berita palsu yang sesuai dengan keyakinan politik mereka, bahkan ketika mereka sadar bahwa berita tersebut tidak sepenuhnya benar.
Yang membuat bias konfirmasi begitu sulit dilawan adalah karena ia bekerja secara tidak sadar. Kita merasa telah bersikap rasional, padahal pikiran kita sudah dipengaruhi oleh keinginan untuk tetap “benar”. Dalam ranah psikologi, ini disebut juga sebagai motivated reasoning, di mana proses berpikir kita lebih dikendalikan oleh emosi dan kepentingan pribadi ketimbang fakta objektif (Kunda, 1990).
Namun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Kesadaran akan adanya bias ini adalah langkah awal. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mencari sumber informasi dari berbagai sisi, dan aktif mempertanyakan keyakinan sendiri merupakan langkah konkret untuk menantang bias konfirmasi. Beberapa program literasi digital bahkan menyarankan teknik berpikir "disconfirmatory", yaitu secara sengaja mencari informasi yang bisa membantah pendapat kita, bukan sekadar menguatkannya.
Lebih jauh, pendidikan dan pelatihan literasi media juga memainkan peran penting. Ketika seseorang dilatih untuk mengevaluasi validitas sumber informasi, memahami konteks, serta mengenali emosi yang bermain dalam proses penilaian, maka peluang untuk terjebak dalam bias konfirmasi akan menurun. Inisiatif seperti “Check, Then Share” atau kampanye verifikasi fakta yang dikembangkan oleh lembaga seperti First Draft dan UNESCO menunjukkan bahwa upaya sistematis bisa membantu publik melawan distorsi informasi akibat bias psikologis ini.
Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa musuh utama dari nalar bukan hanya kebodohan, tetapi keyakinan yang tidak dipertanyakan. Bias konfirmasi adalah fenomena psikologis yang sangat manusiawi, namun dalam era informasi yang serba cepat dan penuh manipulasi, mengenali dan melawannya adalah bagian penting dari pertahanan kita sebagai warga digital yang bertanggung jawab. Sebagai biro psikologi terpercaya, Smile Consulting Indonesia adalah vendor psikotes yang juga menyediakan layanan psikotes online dengan standar profesional tinggi untuk mendukung keberhasilan asesmen Anda.
Referensi:
Wason, P. C. (1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(3), 129–140. https://doi.org/10.1080/17470216008416717
Nickerson, R. S. (1998). Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175
Kunda, Z. (1990). The Case for Motivated Reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480–498. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480
Pennycook, G., & Rand, D. G. (2018). The Implied Truth Effect: Attaching Warnings to a Subset of Fake News Stories Increases Perceived Accuracy of Stories Without Warnings. Management Science, 66(11), 4944–4957. https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3478
UNESCO. (2021). Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners. Retrieved from: https://www.unesco.org/en/media-information-literacy