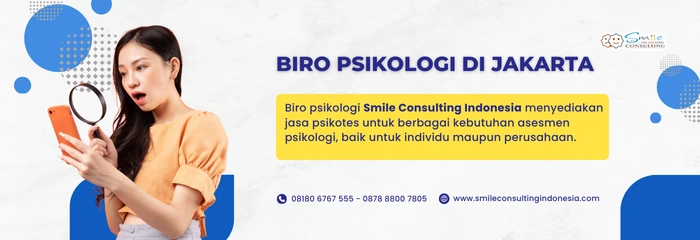Di tengah maraknya disinformasi yang menyebar begitu cepat, muncul pertanyaan yang cukup mengganggu: mengapa orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi, bahkan mereka yang dianggap cerdas secara intelektual, juga bisa terjerat dalam jebakan hoaks? Bukankah mereka seharusnya lebih mampu menyaring informasi dan berpikir kritis? Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa kecerdasan kognitif bukanlah tameng absolut terhadap misinformasi. Ada faktor-faktor psikologis dan sosial yang berperan besar dalam membuat bahkan individu cerdas sekalipun menjadi korban hoaks.
Penelitian menunjukkan bahwa percaya atau tidaknya seseorang terhadap hoaks lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi psikologis dan bias kognitif, ketimbang sekadar tingkat IQ atau pendidikan formal. Lewandowsky et al. (2012) dalam jurnal Psychological Science menjelaskan bahwa seseorang bisa menolak fakta yang valid jika informasi tersebut bertentangan dengan identitas atau nilai ideologis yang ia pegang. Fenomena ini disebut sebagai motivated reasoning, di mana individu secara tidak sadar memilah informasi yang selaras dengan pandangan pribadinya, dan menolak informasi yang bertentangan, meski berasal dari sumber terpercaya.
Dalam konteks ini, orang pintar bisa justru lebih mahir dalam menyusun argumentasi untuk mempertahankan kepercayaannya, termasuk yang keliru. Stanovich dan West (2007) menjelaskan dalam Behavioral and Brain Sciences bahwa kecerdasan analitik dan nalar reflektif merupakan dua sistem berpikir yang berbeda. Seseorang yang memiliki IQ tinggi belum tentu menggunakan sistem reflektif dalam menyikapi informasi, apalagi jika emosinya sudah tersentuh. Maka dari itu, orang pintar bisa lebih ‘cerdas’ dalam merasionalisasi hoaks, bukan membantahnya.
Satu faktor penting lainnya adalah bias konfirmasi (confirmation bias). Ketika seseorang sudah punya keyakinan tertentu, ia cenderung hanya mencari dan mempercayai informasi yang memperkuat keyakinannya, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini terjadi pada siapa saja, termasuk kalangan terpelajar. Bahkan, karena literasi digital yang tinggi, orang pintar lebih mudah menemukan artikel, kutipan, atau bahkan jurnal yang tampak sah untuk mendukung pendapatnya, meskipun konteks atau datanya dipelintir.
Aspek sosial juga memainkan peran besar. Dalam masyarakat yang sangat terpolarisasi, kebenaran sering kali menjadi relatif tergantung siapa yang menyampaikan. Orang bisa lebih percaya informasi dari figur yang ia kagumi atau dari kelompok sosial tempat ia merasa belong. Di sinilah efek echo chamber bekerja: ruang sosial atau digital yang hanya memperkuat satu jenis suara, dan menutup akses terhadap perspektif yang berbeda (Cinelli et al., 2021, PNAS). Dalam lingkungan seperti ini, tidak peduli seberapa cerdas seseorang, ia tetap rentan termakan narasi palsu jika lingkungannya tidak mendukung keterbukaan informasi.
Lebih jauh, kepercayaan pada hoaks juga bisa muncul dari kecemasan sosial dan kebutuhan akan kontrol. Ketika dunia terasa kacau dan penuh ketidakpastian, seperti saat pandemi atau konflik politik, hoaks sering menyajikan penjelasan sederhana yang memberi rasa aman. Dalam kondisi psikologis seperti ini, otak lebih memilih narasi yang meyakinkan meski tidak rasional. Penelitian dari Swire-Thompson & Lazer (2020) menyebutkan bahwa bahkan mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis bisa tetap mempercayai hoaks jika hoaks tersebut menyentuh ketakutan atau harapan mereka yang terdalam.
Apa yang bisa kita pelajari dari kenyataan ini? Bahwa literasi digital dan pendidikan formal penting, tetapi belum cukup. Kita juga perlu menumbuhkan kerendahan hati intelektual dengan kesediaan untuk mengakui bahwa kita bisa salah, serta kemampuan untuk menunda penilaian saat menerima informasi. Pendekatan berbasis empati dan dialog, bukan hanya debat rasional, juga dibutuhkan untuk membantu orang lepas dari jeratan informasi palsu.
Pada akhirnya, tak peduli seberapa cerdas seseorang, otak manusia tetaplah rentan terhadap bias, emosi, dan konteks sosial. Justru dengan memahami kerentanan ini, kita bisa lebih mawas diri dan tidak mudah menghakimi mereka yang terjebak hoaks. Sebab bisa jadi, mereka hanya menggunakan logika dalam ruang emosi yang salah. Sebagai biro psikologi terpercaya, Smile Consulting Indonesia adalah vendor psikotes yang juga menyediakan layanan psikotes online dengan standar profesional tinggi untuk mendukung keberhasilan asesmen Anda.
Referensi:
Lewandowsky, S., Ecker, U. K., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106-131. https://doi.org/10.1177/1529100612451018
Stanovich, K. E., & West, R. F. (2007). Natural myside bias is independent of cognitive ability. Thinking & Reasoning, 13(3), 225-247. https://doi.org/10.1080/13546780600780796
Swire-Thompson, B., & Lazer, D. (2020). Public health and online misinformation: Challenges and recommendations. Annual Review of Public Health, 41, 433–451. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094127
Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. PNAS, 118(9). https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118