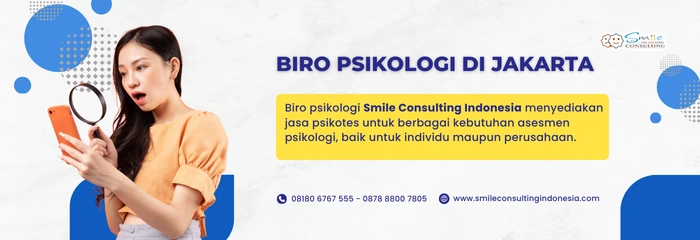Di satu sisi, kita sedang hidup di era dengan kesadaran kesehatan mental yang belum pernah setinggi ini. Di sisi lain, kita juga hidup di zaman di mana satu pencarian Google bisa meyakinkan seseorang bahwa mereka mengidap lima gangguan mental sekaligus. Fenomena ini menjadi paradoks yang tak terhindarkan dalam dunia digital yang penuh informasi sekaligus misinformasi.
Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental memang perlu dirayakan. Pendidikan publik, media sosial, hingga kampanye dari figur publik telah mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam membicarakan kondisi psikologis mereka. Dulu, kata-kata seperti depresi, kecemasan, trauma, atau bipolar dianggap tabu dan hanya dibisikkan di ruang konseling tertutup. Kini, istilah-istilah itu muncul di linimasa TikTok, dibahas dalam thread Twitter, hingga dijadikan bahan diskusi podcast.
Namun, popularitas istilah klinis ini justru membawa tantangan baru: munculnya praktik self-diagnosis yang tidak berbasis pada pemeriksaan profesional, melainkan pada tes daring tanpa validitas, pengalaman personal orang lain di media sosial, atau narasi konten yang menggiring audiens merasa "saya juga kayak gitu, berarti saya punya gangguan ini."
Praktik ini tidak selalu lahir dari kemalasan atau niat buruk. Banyak orang yang sebenarnya mengalami tekanan nyata dan mencoba mencari jawaban di tempat yang paling mudah diakses yakni melalui internet. Masyarakat yang masih memiliki hambatan biaya dan stigma untuk mengakses psikolog, wajar jika banyak yang memilih jalan pintas. Sayangnya, tidak semua konten daring memiliki dasar ilmiah atau etika penyampaian yang memadai.
Contohnya, ketika seseorang merasa kesulitan fokus, mudah bosan, dan sering menunda pekerjaan, ia bisa saja langsung mengklaim diri mengidap ADHD hanya karena melihat video "7 tanda kamu ADHD dan tidak tahu." Atau ketika suasana hati berubah drastis dalam satu hari, ada yang merasa yakin dirinya bipolar, padahal yang terjadi bisa saja kelelahan biasa atau fluktuasi emosi wajar akibat tekanan pekerjaan.
Efek dari self-diagnosis ini bisa berbahaya. Selain memicu kecemasan berlebih dan efek placebo negatif, seseorang bisa salah mengambil kesimpulan tentang dirinya dan terjebak dalam identitas gangguan yang belum tentu dimiliki. Bahkan, ada kasus di mana self-diagnosis membuat individu menolak bantuan profesional karena merasa sudah tahu penyebabnya dan bisa "mengobati diri sendiri."
Lebih dari itu, budaya ini dapat menciptakan semacam romantisasi gangguan mental, di mana kondisi psikologis dianggap sebagai bagian dari estetika, identitas, atau bahkan daya tarik. Ini terlihat dari maraknya konten yang menampilkan gangguan mental dengan visual menarik, musik melankolis, dan narasi puitis. Alih-alih mendorong pemulihan, konten semacam ini malah mengaburkan batas antara kesadaran dan glorifikasi.
Maka, yang perlu dilakukan bukan mematikan suara di internet, melainkan mendampingi kesadaran dengan edukasi yang benar. Literasi kesehatan mental harus berkembang seiring popularitasnya. Masyarakat perlu diajak membedakan antara refleksi emosional biasa dengan gangguan klinis yang memerlukan diagnosis profesional. Akses pada tenaga ahli kesehatan jiwa juga perlu ditingkatkan, baik dari sisi biaya, ketersediaan, maupun stigma.
Psikolog dan psikiater pun perlu lebih hadir di ruang digital. Bukan untuk "menangkal" konten viral semata, tapi memberikan penyeimbang dari informasi yang beredar. Konten yang mengedukasi, menjelaskan gejala secara bertanggung jawab, serta mendorong pemeriksaan yang valid adalah kunci untuk meminimalisir dampak negatif dari tren self-diagnosis online.
Kesadaran adalah langkah awal, tapi ia harus dituntun agar tak tersesat dalam kabut informasi. Internet boleh jadi ruang awal untuk mengenali diri, tapi bukan tempat akhir untuk memberi label pada kesehatan mental seseorang. Biro psikologi Smile Consulting Indonesia menyediakan jasa psikotes untuk berbagai kebutuhan asesmen psikologi, baik untuk individu maupun perusahaan. Layanan kami dirancang untuk memberikan hasil yang akurat dan terpercaya.
Referensi:
Paris, J. (2023). The dangers of self-diagnosis via social media. Current Psychiatry Reports. https://doi.org/10.1007/s11920-023-01335-6
National Institute of Mental Health (NIMH). (2022). Mental Health Information. Retrieved from https://www.nimh.nih.gov/health
APA (American Psychological Association). (2021). Understanding mental health diagnosis. https://www.apa.org/topics/mental-health