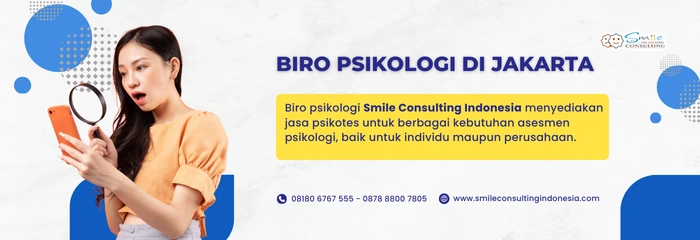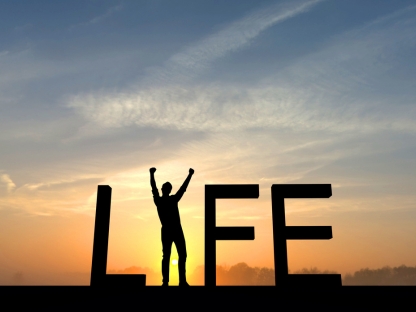Di era digital saat ini, informasi beredar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, di balik derasnya arus informasi tersebut, tersembunyi fenomena yang kian mengkhawatirkan: penyebaran hoax yang tak hanya masif, tapi juga sangat sulit dihentikan. Jika ditelusuri lebih dalam, penyebab utama dari cepatnya hoaks menyebar bukan hanya karena teknologi atau literasi yang rendah, melainkan karena faktor psikologis yang lebih dalam: emosi negatif. Ketakutan, kemarahan, rasa jijik, dan kecemasan terbukti menjadi pendorong kuat dalam mendorong orang untuk memberikan informasi palsu, bahkan tanpa sempat memverifikasi kebenarannya.
Sebuah studi penting yang dilakukan oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) di jurnal Science mengungkap bahwa hoaks menyebar secara signifikan lebih cepat, luas, dan dalam daripada kebenaran. Menariknya, salah satu alasan utama adalah karena hoaks lebih mampu memancing respons emosional, terutama emosi negatif seperti rasa takut dan kejutan. Hoax sering kali dikemas dengan judul sensasional, narasi tragis, atau bahaya yang mengancam langsung kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang merasa takut atau marah, bagian otak yang terlibat dalam proses berpikir kritis cenderung melemah, sementara respons otomatis untuk bereaksi secara cepat justru mengambil alih.
Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan erat dengan emotional contagion, yaitu kecenderungan emosi seseorang menyebar dan mempengaruhi orang lain secara tidak sadar. Ketika seseorang merasa terancam oleh berita hoax ia cenderung memberikan informasi itu sebagai bentuk pelampiasan kecemasan atau sebagai upaya memperingatkan orang lain, walau belum tentu informasi tersebut benar. Penelitian Ferrara dan Yang (2015) bahkan menyebutkan bahwa pengguna media sosial lebih mungkin menyebarkan konten yang memicu emosi negatif karena algoritma media sosial cenderung memperkuat keterlibatan terhadap konten semacam itu.
Lebih jauh lagi, emosi negatif juga mempersempit perhatian dan memperkuat bias kognitif. Misalnya, dalam kondisi marah atau takut, seseorang cenderung hanya memperhatikan informasi yang sesuai dengan persepsi atau keyakinannya. Ini disebut sebagai motivated reasoning, di mana emosi mendahului logika. Di tengah situasi sosial yang tegang, misalnya menjelang pemilu atau saat krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19, emosi kolektif seperti panik dan kemarahan menciptakan ekosistem sempurna bagi hoaks untuk tumbuh subur. Tidak mengherankan jika informasi palsu tentang vaksin, politik, atau bencana alam lebih mudah viral ketimbang klarifikasinya.
Dalam konteks media sosial, algoritma juga berperan dalam memperkuat siklus ini. Platform digital secara otomatis memprioritaskan konten yang memicu interaksi tinggi, dan konten yang mengandung emosi negatif, seperti kemarahan atau kecemasan, cenderung menghasilkan lebih banyak komentar, reaksi, dan pembagian. Penelitian Brady et al. (2017) dalam PNAS menunjukkan bahwa moral outrage (kemarahan moral) dalam unggahan media sosial meningkatkan kemungkinan konten tersebut dibagikan secara signifikan. Dengan demikian, penyebaran hoaks sering kali bukanlah sebuah kesalahan teknis, melainkan hasil interaksi antara psikologi manusia dan desain sistem digital.
Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap peran emosi dalam penyebaran hoaks masih sangat terbatas. Banyak orang percaya bahwa mereka membagikan informasi karena niat baik atau rasa peduli, tanpa menyadari bahwa mereka sedang terdorong oleh emosi sesaat yang mengaburkan logika. Di sinilah pentingnya literasi emosi, yaitu kemampuan mengenali dan mengelola emosi sendiri sebelum mengambil tindakan impulsif, termasuk dalam membagikan informasi. Pendidikan literasi digital pun perlu diperluas cakupannya, tidak hanya mengajarkan cara memverifikasi berita, tapi juga mengajak masyarakat untuk memahami bagaimana emosi mempengaruhi penilaian dan perilaku mereka di ruang digital.
Dalam menghadapi hoax, strategi terbaik bukan hanya mengandalkan cek fakta atau teknologi deteksi otomatis, melainkan juga membangun ketahanan psikologis masyarakat. Ketahanan ini tidak hanya berarti kuat secara emosional, tetapi juga mampu mengenali ketika emosi pribadi sedang dieksploitasi oleh informasi palsu. Dengan kesadaran tersebut, masyarakat akan lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam arus hoaks yang dibalut oleh emosi negatif.
Hoax menyebar bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi karena manusia adalah makhluk emosional. Untuk melawan hoaks secara efektif, kita tidak hanya perlu melatih pikiran kritis, tapi juga mengelola perasaan dengan lebih bijak. Di era digital, mengendalikan emosi bukan hanya kunci hubungan personal yang sehat, tapi juga pertahanan utama terhadap disinformasi. Sebagai biro psikologi terpercaya, Smile Consulting Indonesia adalah vendor psikotes yang juga menyediakan layanan psikotes online dengan standar profesional tinggi untuk mendukung keberhasilan asesmen Anda.
Referensi:
Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559
Ferrara, E., & Yang, Z. (2015). Measuring emotional contagion in social media. PLOS ONE, 10(11), e0142390. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142390
Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. PNAS, 114(28), 7313–7318. https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114
Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. PNAS, 111(24), 8788–8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111