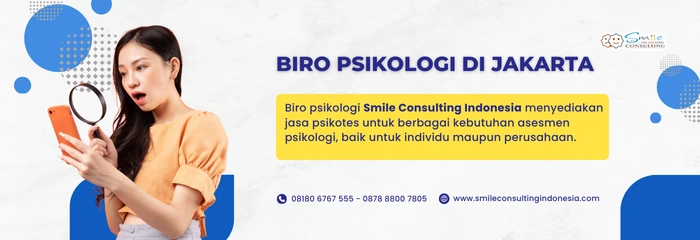Dalam era digital saat ini, informasi menyebar lebih cepat daripada sebelumnya. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Disinformasi telah menjadi ancaman serius terhadap kehidupan sosial, politik, dan bahkan kesehatan publik. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa kita begitu mudah mempercayai, bahkan menyebarkan, informasi yang tidak benar? Jawabannya terletak pada cara kerja pikiran manusia.
Secara psikologis, otak kita tidak selalu berfungsi seperti mesin pencari yang objektif. Sebaliknya, ia lebih menyerupai filter yang mengutamakan informasi yang terasa relevan secara emosional, mudah dipahami, atau sesuai dengan keyakinan yang telah kita miliki sebelumnya. Salah satu konsep utama dalam hal ini adalah ‘bias kognitif’ dimana ada kecenderungan sistematis dalam berpikir yang sering kali menyesatkan logika kita. Misalnya, 'confirmation bias' atau bias konfirmasi membuat kita lebih mudah menerima informasi yang mendukung opini kita, dan menolak yang bertentangan dengannya.
Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa emosi memainkan peran besar dalam penyebaran disinformasi. Informasi yang menimbulkan rasa takut, marah, atau jijik cenderung lebih mudah viral dibandingkan fakta-fakta yang netral. Ini karena emosi tersebut memicu reaksi cepat dari otak kita, yang kemudian mendorong kita untuk memberikan informasi tersebut sebagai bentuk 'peringatan' kepada orang lain. Dalam konteks ini, menyebarkan hoax bisa jadi bukan karena niat jahat, melainkan karena dorongan emosional yang kuat.
Di samping faktor emosi dan kognisi, ada pula tekanan sosial. Media sosial memperkuat efek ini. Ketika informasi dibagikan oleh teman, keluarga, atau tokoh yang kita kagumi, kita cenderung mempercayainya tanpa mengecek kebenarannya. Lebih dari itu, kita sering merasa perlu 'ikut serta' dalam arus percakapan agar tidak tertinggal atau dikucilkan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai 'social conformity' yaitu kecenderungan mengikuti arus kelompok meskipun kita ragu akan isinya.
Tak hanya itu, cara platform digital dirancang juga memperkuat penyebaran hoaks. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang membuat kita betah dan terlibat, bukan yang paling benar. Maka, ketika seseorang menyukai atau membagikan hoaks, algoritma akan menampilkan lebih banyak konten serupa. Inilah yang membentuk 'filter bubble' atau 'echo chamber', yaitu ruang informasi yang memperkuat keyakinan kita sendiri dan menutup akses ke sudut pandang yang berbeda.
Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan disinformasi? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita semua rentan. Menyadari bias diri sendiri adalah kunci untuk menjadi pembaca kritis. Kedua, kita bisa melatih keterampilan literasi digital dan berpikir kritis: memeriksa sumber, mencari konfirmasi dari situs terpercaya, dan menahan diri untuk tidak langsung memberikan informasi yang memicu emosi. Ketiga, kita perlu menciptakan budaya diskusi yang sehat di mana orang merasa aman untuk bertanya, mengklarifikasi, dan tidak langsung menghakimi.
Menghadapi disinformasi bukan semata-mata soal teknologi, tapi juga soal psikologi. Semakin kita memahami bagaimana otak kita bekerja, semakin besar peluang kita untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Di tengah gelombang informasi yang deras, kemampuan untuk memilah mana yang benar dan mana yang manipulatif adalah bentuk literasi yang tak kalah penting dari membaca dan menulis itu sendiri. Sebagai bagian dari pusat asesmen Indonesia, biro psikologi Smile Consulting Indonesia menghadirkan solusi asesmen psikologi dan psikotes online berkualitas tinggi untuk kebutuhan evaluasi yang komprehensif.
Referensi:
Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the 'Post-Truth' Era. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(4), 353–369.
Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). The Implied Truth Effect: Attaching Warnings to a Subset of Fake News Stories Increases Perceived Accuracy of Stories Without Warnings. Management Science, 66(11), 4944–4957.
Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. Science, 359(6380), 1146–1151.
World Health Organization. (2022). Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation. https://www.who.int/