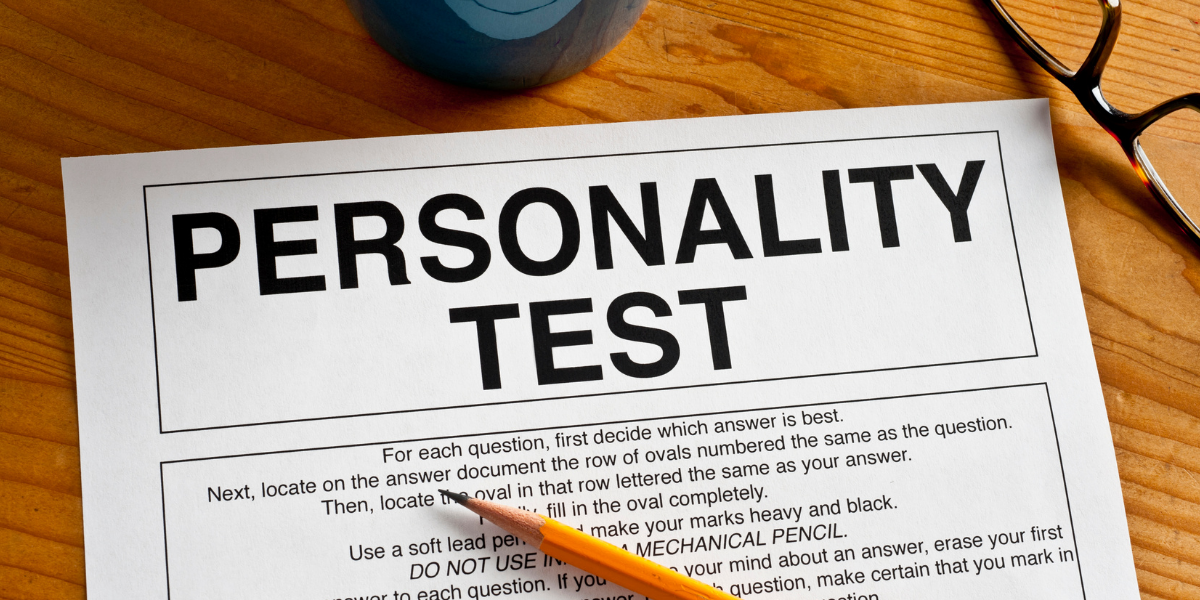Setiap kali musim ujian nasional atau seleksi masuk perguruan tinggi tiba, suasana sekolah dan rumah berubah drastis. Jam belajar bertambah, ruang bimbingan belajar padat, grup WhatsApp orang tua penuh dengan info soal-soal latihan, dan wajah-wajah murid mulai menunjukkan gejala kelelahan. Di balik semangat belajar yang terlihat di permukaan, banyak pelajar sebenarnya sedang bergumul dengan tekanan berat yang jarang dibicarakan: stres akademik.
Stres akademik bukan hanya persoalan nilai rendah atau kesulitan dalam memahami pelajaran. Ia adalah tekanan psikologis yang muncul akibat tuntutan untuk terus berprestasi di tengah sistem pendidikan yang kompetitif dan ekspektasi lingkungan yang tinggi. Banyak siswa mengalaminya ketika mereka merasa hasil belajar mereka menentukan bukan hanya masa depan pribadi, tapi juga harapan orang tua, gengsi keluarga, bahkan martabat sekolah.
Di Indonesia, fenomena ini makin terasa sejak masuknya kurikulum berbasis kompetensi dan diberlakukannya seleksi ketat seperti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) untuk masuk perguruan tinggi negeri. Tidak hanya siswa kelas 12 yang merasakannya, bahkan siswa SMP sudah mulai dibiasakan dengan ritme belajar yang padat dan tekanan agar bisa masuk SMA favorit. Sebuah studi yang dilakukan di beberapa SMA di Yogyakarta menunjukkan bahwa lebih dari 40% siswa mengalami stres akademik dalam tingkat sedang hingga berat, dengan gejala utama berupa kelelahan, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan motivasi belajar (Pratiwi et al., 2020).
Yang membuat tekanan ini semakin rumit adalah adanya ekspektasi dari orang tua. Dalam banyak keluarga, pendidikan masih dianggap sebagai satu-satunya jalan mobilitas sosial. Maka, orang tua tanpa sadar meletakkan beban yang sangat tinggi kepada anak-anak mereka. Kalimat seperti “Harus bisa masuk UI,” atau “Papa sudah kerja keras, kamu jangan gagal,” meskipun dimaksudkan sebagai motivasi, justru sering membuat anak merasa takut, tidak cukup baik, atau cemas gagal membahagiakan orang tua. Beberapa pelajar bahkan lebih takut mengecewakan orang tua daripada gagal ujian itu sendiri.
Tak hanya dari rumah, tekanan juga datang dari sekolah dan lingkungan sosial. Sistem ranking, perlombaan akademik, serta perbandingan antar siswa masih menjadi budaya yang dominan. Belum lagi pengaruh media sosial yang secara tidak langsung menampilkan keberhasilan orang lain sebagai standar yang harus dicapai. Saat teman sebaya mulai mengunggah hasil try out tinggi atau diterima di universitas luar negeri, sebagian siswa mulai meragukan diri sendiri, merasa tertinggal, dan mempertanyakan kemampuan mereka.
Dalam kondisi seperti ini, tidak heran jika stres akademik membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental siswa. Beberapa menunjukkan gejala psikosomatik seperti sakit kepala, maag, atau sulit tidur menjelang ujian. Yang lain mengalami burnout, kehilangan minat belajar, dan menjauhi kegiatan sosial. Bahkan, pada kasus yang ekstrem, stres berkepanjangan bisa memicu kecemasan kronis atau depresi. Di Jepang dan Korea Selatan, dua negara dengan sistem pendidikan kompetitif, kasus bunuh diri akibat stres akademik menjadi perhatian nasional.
Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Beberapa sekolah mulai menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis, dengan menyeimbangkan aspek kognitif dan emosional. Konseling psikologis mulai tersedia di sejumlah sekolah, meski belum merata. Guru pun semakin banyak yang menyadari pentingnya memberi dukungan emosional kepada siswa, bukan sekadar menuntut capaian nilai. Di luar sekolah, komunitas belajar mandiri dan forum diskusi antar pelajar menjadi ruang alternatif untuk saling berbagi tekanan.
Bagi siswa sendiri, mengenali dan memahami emosi yang mereka alami adalah langkah awal penting. Banyak dari mereka yang belum bisa membedakan antara rasa lelah biasa dan tanda-tanda stres kronis. Dengan bantuan guru, konselor, atau orang dewasa terpercaya, mereka bisa mulai memetakan sumber tekanan dan mencari cara mengelolanya. Teknik manajemen waktu, latihan relaksasi, serta membatasi perbandingan sosial juga bisa menjadi langkah praktis untuk mengurangi beban.
Peran orang tua pun tak kalah penting. Dibanding sekadar menuntut hasil, orang tua bisa mulai belajar mendengarkan proses. Menanyakan apa yang anak rasakan, bukan hanya apa yang mereka capai. Menghargai usaha, bukan hanya nilai, karena pada akhirnya, pendidikan seharusnya membangun manusia yang utuh, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara mental dan bahagia menjalani hidupnya.
Masa sekolah memang tidak pernah lepas dari tekanan. Tapi tekanan tidak harus selalu berarti penderitaan. Dengan sistem yang mendukung, relasi yang sehat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang stres akademik, anak-anak kita bisa belajar bukan hanya untuk menghadapi ujian sekolah, tetapi juga ujian kehidupan. Sebagai bagian dari pusat asesmen Indonesia, biro psikologi Smile Consulting Indonesia menghadirkan solusi asesmen psikologi dan psikotes online berkualitas tinggi untuk kebutuhan evaluasi yang komprehensif.
Referensi:
Pratiwi, S. R., Ratnasari, S. L., & Darmawan, I. (2020). Tingkat Stres Akademik dan Strategi Coping Siswa SMA di Yogyakarta. Jurnal Psikologi Indonesia, 17(2), 121–130.
World Health Organization (2021). Adolescent mental health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
Latha, K. S., Reddy, H., & Lakshmi, P. V. (2022). Academic Stress and Mental Health among High School Students: A Review. Indian Journal of Youth and Adolescent Health, 9(1).
Child Mind Institute. (2023). School Stress is Real for Kids. https://childmind.org/article/school-stress-is-real-for-kids/