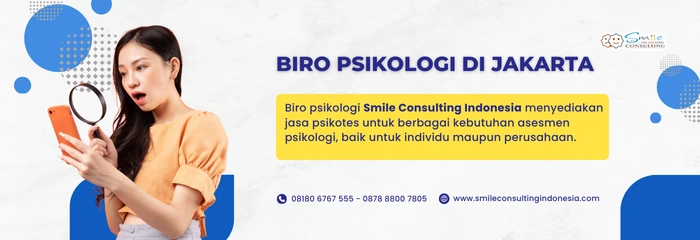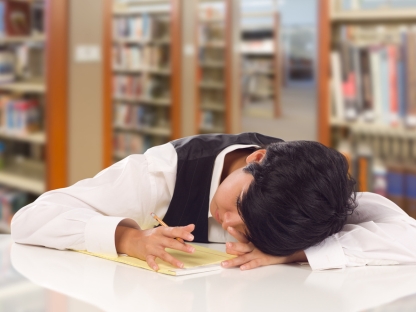Di era digital, informasi menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun yang mencengangkan bukan hanya kecepatan penyebaran itu, melainkan fakta bahwa informasi yang keliru, atau hoaks, sering kali menyebar jauh lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam daripada kebenaran itu sendiri. Fenomena ini bukan hanya masalah teknologi atau algoritma, melainkan menyangkut kecenderungan psikologis manusia yang tertarik pada hal-hal mengejutkan, emosional, dan mengkonfirmasi keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya.
Salah satu studi besar yang mengungkap hal ini dilakukan oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) dari MIT. Dalam studi mereka terhadap lebih dari 126 ribu rumor yang tersebar di Twitter selama satu dekade, ditemukan bahwa berita bohong memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk di-retweet daripada berita faktual. Bahkan, dibutuhkan enam kali lebih cepat bagi hoaks untuk mencapai 1.500 orang pertama dibandingkan berita yang benar. Penjelasan utamanya bukan terletak pada bot atau akun palsu, melainkan pada perilaku manusia itu sendiri.
Secara psikologis, manusia tertarik pada informasi yang menimbulkan kejutan dan emosi kuat seperti rasa takut, marah, atau kagum. Hoaks cenderung dirancang untuk memicu respons emosional semacam ini. Menurut teori “epistemic vigilance” yang dikemukakan oleh Sperber et al. (2010), manusia memiliki mekanisme kognitif untuk menyeleksi informasi yang dipercaya, namun mekanisme ini dapat dilewati ketika informasi terasa relevan secara emosional atau sesuai dengan harapan sosial. Artinya, saat kita merasa informasi itu “masuk akal” secara emosional, kita cenderung tidak memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu.
Selain itu, hoaks seringkali membentuk narasi yang lebih sederhana dan lebih dramatis daripada fakta. Dalam psikologi kognitif, dikenal istilah cognitive ease, yaitu kecenderungan otak untuk menerima informasi yang mudah diproses dan dicerna. Fakta-fakta ilmiah sering kali kompleks, berisi nuansa, atau membutuhkan latar belakang pengetahuan, sedangkan hoaks menyajikan versi “hitam-putih” yang lebih mudah dipahami dan dibagikan. Fenomena ini juga diperkuat oleh bias konfirmasi, yakni kecenderungan kita untuk mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan yang sudah kita miliki sebelumnya (Nickerson, 1998).
Dalam konteks sosial media, platform seperti Facebook, TikTok, dan X (dulu Twitter), memiliki algoritma yang menyukai interaksi: semakin banyak yang menyukai, mengomentari, dan membagikan, semakin sering konten itu muncul. Karena hoaks biasanya memancing respons emosional yang tinggi, mereka cenderung mendapatkan lebih banyak interaksi dan secara algoritmik tersebar lebih luas. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana konten palsu mendapatkan panggung lebih besar dibandingkan klarifikasi atau informasi faktual.
Dampaknya tidak ringan. Hoaks kesehatan misalnya, dapat mendorong orang menolak vaksin, mengadopsi pengobatan berbahaya, atau panik secara massal. Di masa pandemi COVID-19, misinformasi bahkan diakui WHO sebagai “infodemic” yaitu epidemi informasi salah yang mengganggu respon kesehatan masyarakat (Zarocostas, 2020). Dalam politik, hoaks bisa memecah belah masyarakat, menurunkan kepercayaan pada lembaga publik, dan mendorong perilaku agresif.
Solusi terhadap penyebaran hoaks tidak bisa hanya diserahkan pada teknologi atau pemerintah. Perlu pendidikan literasi digital yang dimulai sejak usia dini, membiasakan individu untuk berpikir kritis, mengecek sumber informasi, dan mengenali bias kognitif dalam dirinya sendiri. Penelitian dari Lewandowsky et al. (2012) menekankan pentingnya pre-bunking, yaitu memberikan informasi faktual sebelum seseorang terpapar hoaks, untuk mengurangi efek misinformasi. Upaya ini juga harus ditunjang oleh platform media sosial yang proaktif dalam menyaring konten berbahaya, serta jurnalisme yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.
Pada akhirnya, memahami mengapa hoaks menyebar lebih cepat bukan hanya soal melihat kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang memahami kerentanan psikologis kita sebagai manusia. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih waspada terhadap informasi yang kita terima, bagikan, dan percayai, karena tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang benar akan viral. Sebagai bagian dari pusat asesmen Indonesia, biro psikologi Smile Consulting Indonesia menghadirkan solusi asesmen psikologi dan psikotes online berkualitas tinggi untuk kebutuhan evaluasi yang komprehensif.
Referensi:
Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559
Sperber, D., Clement, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origgi, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic vigilance. Mind & Language, 25(4), 359–393.
Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220.
Zarocostas, J. (2020). How to fight an infodemic. The Lancet, 395(10225), 676.
Lewandowsky, S., Ecker, U. K., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106–131.